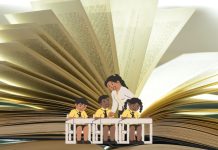Lidya Nurjannah
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
Universitas Pamulang
SERANG – Sudah lebih dari satu dekade Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menjadi rujukan hukum utama dalam upaya pelestarian alam di Indonesia. UU ini lahir sebagai respons atas meningkatnya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali.
Namun, pertanyaan penting yang masih bergema hingga kini: apakah undang-undang ini sudah cukup kuat menahan laju krisis ekologis? UU No. 32/2009 sejatinya memuat semangat besar: perlindungan lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, partisipatif, keadilan, dan tanggung jawab.
Keberadaan instrumen lingkungan hidup, seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), serta sanksi administratif hingga pidana bagi perusak lingkungan, memperlihatkan betapa negara ingin hadir secara tegas.
Namun, implementasi selalu menjadi titik lemah. Banyak pelanggaran lingkungan, dari pencemaran sungai hingga deforestasi besar-besaran, yang tidak ditindak dengan tegas. Beberapa kasus bahkan menunjukkan adanya tumpang tindih kepentingan antara investasi dan pelestarian, di mana lingkungan sering dikorbankan atas nama “pembangunan nasional”.
Di sinilah peran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diuji. KLHK sebagai garda terdepan perlindungan lingkungan tidak hanya bertugas mengeluarkan izin atau melakukan pengawasan, melainkan juga harus proaktif dalam edukasi, pencegahan konflik, serta penegakan hukum.
Salah satu tantangan utama KLHK hari ini adalah bagaimana memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat sipil agar pelaksanaan UU ini tidak sekadar menjadi jargon administratif.
Transparansi dan partisipasi publik juga menjadi kunci. Proyek-proyek besar yang berdampak ekologis tinggi seharusnya tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan masyarakat lokal dan penilaian lingkungan yang komprehensif. Selain itu, publik perlu diberikan akses yang memadai untuk mengawasi, melapor, dan menuntut keadilan lingkungan.
Ke depan, evaluasi terhadap UU No. 32/2009 menjadi penting untuk menyesuaikan dengan tantangan baru, seperti krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan ketimpangan ekologis. Pembaruan regulasi harus berpihak pada keberlanjutan, bukan hanya pada kelancaran investasi. Indonesia tidak kekurangan regulasi, tetapi sering kekurangan ketegasan dalam pelaksanaan.
Jika KLHK benar-benar ingin menjadi pemegang mandat “penjaga bumi” Indonesia, maka ia harus lebih berani bersuara untuk lingkungan, bahkan ketika harus berhadapan dengan kekuatan ekonomi dan politik besar. Sudah waktunya kita menempatkan lingkungan hidup bukan sebagai penghalang pembangunan, melainkan sebagai fondasi utama peradaban masa depan. UU No. 32 Tahun 2009 adalah alat penting, tapi hanya akan bermakna jika dihidupkan dengan komitmen dan keberanian politik yang nyata.